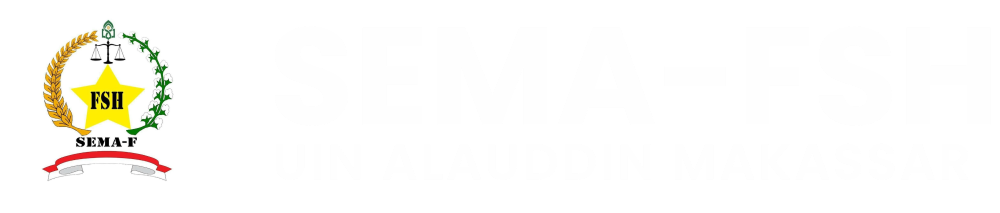Di negara yang mengklaim diri sebagai negara hukum, hukum semestinya menjadi instrumen utama untuk menegakkan keadilan dan melindungi rakyat. Namun di Indonesia, kenyataan sering berkata lain. Penegakan hukum masih terlihat berat sebelah: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ungkapan ini bukan lagi metafora, melainkan kenyataan yang dapat dibuktikan dengan sederet data dan fakta.
Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata vonis terhadap terdakwa korupsi hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Dari 830 perkara korupsi yang disidangkan, 74% terdakwanya divonis ringan, bahkan sebagian di antaranya hanya menjalani hukuman percobaan. Kontras dengan pelaku pencurian kecil yang bisa dihukum bertahun-tahun demi sesuap nasi. Ini adalah ketimpangan yang merusak rasa keadilan publik.
Contohnya bisa kita lihat dari kasus Harvey Moeis, tersangka korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, namun hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara. Atau kasus eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang meski menerima suap miliaran rupiah, vonisnya bolak-balik dikurangi, dan kini hanya tinggal 5 tahun penjara. Bandingkan dengan negara seperti Tiongkok atau Korea Selatan, yang menghukum koruptor puluhan tahun atau bahkan hukuman mati dalam kasus besar.
Fakta-fakta ini membuat publik semakin kehilangan kepercayaan pada institusi penegak hukum. Bukan hanya karena hukum tak ditegakkan secara adil, tetapi karena ia tampak mudah dikompromikan oleh kekuasaan dan uang. Saat hukum lebih melindungi pelaku kejahatan kelas atas ketimbang korban, keadilan menjadi barang mewah.
Namun, kehilangan kepercayaan bukan berarti kita boleh kehilangan harapan. Reformasi hukum masih mungkin diperjuangkan—asal ada kemauan politik dan tekanan publik yang cukup kuat. Penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan KPK harus disertai dengan transparansi proses hukum. Proses legislasi juga harus dibuka lebar untuk partisipasi masyarakat sipil dan tidak dikendalikan oleh kepentingan elite.
Media massa memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan. Lewat pelaporan investigatif, edukasi hukum, hingga opini publik, media bisa menjadi corong keberpihakan pada keadilan. Demikian pula masyarakat sipil yang harus terus bersuara, mengawasi, dan menolak kompromi terhadap ketidakadilan.
Supremasi hukum bukan sekadar jargon konstitusi. Ia adalah tiang penyangga negara. Jika hukum tak lagi bisa dipercaya, maka negara kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya. Pertanyaannya kini bukan hanya apakah hukum bisa ditegakkan, tetapi apakah kita masih bersedia memperjuangkannya?