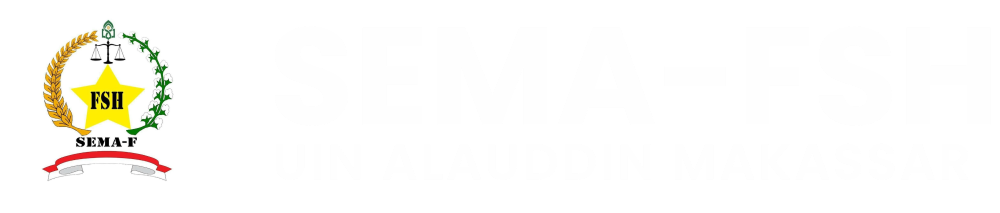Setiap krisis legitimasi selalu memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana rakyat percaya pada kekuasaan yang ada, dan sejauh mana pemangku kebijakan mampu mempertahankan wibawa tanpa menyingkap wajah represifnya? Demokrasi jalanan, dengan segala kebisingannya, lahir dari jarak yang semakin menganga antara janji politik dan realitas kehidupan sehari-hari, antara retorika manis dan kepahitan hidup sehari-hari. Alih-alih membaca demonstrasi sebagai penanda vitalitas demokrasi, penguasa menanggapinya sebagai ancaman yang harus dibungkam. Dari titik inilah lahir strategi pengendalian ganda: menghadirkan ketakutan di jalanan melalui instrumen aparat represif, sekaligus menebar gentar di dunia maya lewat rezim algoritmik.
Ketika terjadi pecah kongsi politik dan konflik kepentingan, negara memainkan hegemoni dengan cermat: memanipulasi simpati, empati, dan rasa takut, sehingga rakyat merasa cemas sekaligus marah. Narasi media dikontrol algoritma, membentuk persepsi bahwa demonstrasi adalah gangguan ketertiban, bukan kritik substansial. Aparat keamanan dikerahkan bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk memproduksi ketakutan. Gas air mata, water cannon, pengroyokan, hingga penangkapan demonstran menjadi ritual yang memberi pesan jelas: menentang negara berisiko nyawa, penjara, dan stigma sosial. Jalanan yang seharusnya menjadi ruang artikulasi rakyat disulap menjadi panggung represi, tempat rakyat belajar menundukkan kepala sebelum berani bersuara.
Di ruang digital, ketakutan bekerja dengan cara lebih halus namun tak kalah mematikan. Negara bersekutu dengan korporasi teknologi untuk menyalakan algoritma yang membentuk alur wacana publik. Suara kritis hilang dari lini masa, unggahan yang mengungkap ketidakadilan dilabeli hoaks, serangan buzzer terorganisir, hingga muncul ancaman digital yang menakutkan. Demokrasi digital yang seharusnya menjadi medan kebebasan justru menjelma menjadi instrumen domestikasi, di mana rakyat menyadari bahwa ruang maya pun telah dikontrol logika kekuasaan.
Antonio Gramsci menekankan bahwa kekuasaan bertahan bukan hanya melalui represi fisik, tetapi juga melalui hegemoni yang membuat masyarakat menerima ketundukan sebagai wajar. Hegemoni ketakutan adalah bentuk mutakhir dari dominasi ini: rakyat dicekoki gagasan bahwa melawan tidak ada gunanya, bahwa diam lebih aman daripada bersuara, bahwa demonstrasi hanya merugikan. Jean-Paul Sartre menambahkan dimensi eksistensial: manusia bebas, tetapi kebebasannya sering dibatasi oleh situasi. Individu yang menghadapi intimidasi memilih diam bukan karena tak ada pilihan, tetapi karena terjebak dalam alienasi yang menipu diri sendiri, merasa ragu dan secara tidak langsung ikut memilih diam, sejatinya ia telah menyerahkan kebebasan fundamentalnya kepada logika ketakutan.
Friedrich Engels menegaskan bahwa ideologi selalu berakar pada struktur ekonomi-politik. Rezim algoritmik lahir dari persekutuan negara dan kapital digital, berfungsi untuk menegakkan “normalitas” yang menguntungkan kelas penguasa. Demonstrasi dituduh merusak ketertiban, padahal yang sebenarnya dijaga adalah tatanan ekonomi-politik yang menopang elit. Machiavelli, dalam Il Principe, menegaskan bahwa penguasa harus menjadi singa sekaligus rubah: singa menakuti tubuh, rubah menyesatkan pikiran. Aparat di jalanan menjadi singa yang mengintimidasi fisik, algoritma menjadi rubah yang membelokkan persepsi. Bersama-sama, keduanya membuat rakyat merasa kalah sebelum bertarung.
Paradoks negara modern muncul jelas: alih-alih fokus pada substansi tuntutan, negara lebih khawatir pada dampak dari rusaknya fasilitas publik, kemacetan, terganggunya aktivitas ekonomi, dan citra di mata investor. Padahal itu hanyalah gejala, bukan akar masalah. Tuntutan rakyat tentang ketidakadilan, kesenjangan, korupsi, dan penindasan diabaikan. Negara justru menutup telinga, sibuk menguatkan cengkeraman kekuasaan. Gramsci mengingatkan hegemoni yang rapuh membutuhkan represi untuk bertahan. Semakin represif negara, semakin jelas rapuhnya legitimasi.
Solusi menghadapi hegemoni ketakutan memang kompleks. Pertama, rakyat harus membongkar mekanisme ketakutan melalui solidaritas grass root. Demonstrasi harus menjadi gerakan historis yang melibatkan berbagai elemen: masyarakat, mahasiswa, pekerja, tenaga medis, media independen, hingga komunitas lintas kelas. Ketakutan fisik kehilangan daya ketika rakyat tahu mereka tidak sendirian. Kedua, di ruang digital, rakyat harus membangun kontra-hegemoni melalui jaringan informasi alternatif, produksi narasi tandingan, monitoring dan kontroling narasi tandingan. Demokrasi digital harus diperjuangkan, bukan diterima pasif. Ketiga, negara harus menyadari bahwa demonstrasi adalah barometer partisipasi rakyat. Ia adalah sinyal luka sosial yang harus dijawab secara substantif, bukan ditindas.
Sejarah membuktikan bahwa hegemoni ketakutan tidak bertahan lama. Dari revolusi Perancis, bolsevik hingga Arab Spring, rakyat selalu menemukan cara melewati rasa takut. Ketika ketakutan tak lagi mempan, represi menjadi bahan bakar keberanian rakyat. Negara yang membangun kekuasaan di atas ketakutan hanya menunda kehancurannya.
Akhirnya, inti persoalan bukan apakah negara mampu menjinakkan demokrasi jalanan melalui singa dan rubah, melainkan sejauh mana negara mau mendengar rakyat. Demokrasi hanya bernapas dalam kebebasan. Jika negara ingin keluar dari krisis legitimasi, satu-satunya jalan adalah mendengar tuntutan rakyat, bukan menakut-nakuti mereka.
Suara rakyat, betapapun ditekan, akan selalu menemukan jalannya, di ruang digital, dalam sejarah, dan di jalanan.